PENULIS : DRS. ABD. GHAFFAR. MA
(DOSEN IAIN STS. JAMBI)
A. Pendahuluan
Al-Qur’an sebagai hudan li al-nas (petunjuk bagi manusia) merupakan referensi utama dalam sains keislaman. Ketika al-Qur’an dikaitkan dengan sumber ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan manusia di dunia ini, maka pada saat itu ia berada pada posisi tibyan li kulli syai (penjelasan tentang segala sesuatu) yang paling utama sebagai rujukan dalam kehidupan manusia. Sedangkan Rasulullah Saw –dalam kontek ini- merupakan referensi kedua yang menempati posisi sebagai mubayyin (Orang yang menjelaskan) mengenai maksud, tujuan dan target yang dikehendaki makna-makna tersurat dan tersirat di dalam ayat-ayat al-Qur’an. Penjelasan-penjelasan Rasulullah Saw kepada manusia tentang isi kandungan al-Qur’an dikenal dalam terma tafsir sebagai tibyan li al-nas (penjelasan bagi manusia) yang kemudian disebut dengan Hadits Rasulullah Saw . Al-Qur'an sebagai Tibyan li Kulli Syai dan Hadits Rasulullah Saw sebagai tibyan li al-nas dalam terma ilmu tafsir disebut juga dengan istilah al-tafsir bi al-ma'tsur atau al-tafsir bi al-riwayah . Oleh karena Rasulullah Saw., pada masa hidupnya melarang sahabat-sahabatnya untuk menulis hadits-haditsnya lantaran adanya kekhawatiran akan bercampur aduk dengan ayat-ayat al-Qur’an yang pada saat itu proses nuzul al-Qur’an sedang berlangsung. Maka para sahabatnya pada saat itu hanya menghafal hadits-hadits yang mereka dengar dan yang mereka saksikan langsung dari beliau sampai akhir hayatnya. Kondisi seperti ini –sebagaimana disebut dalam sejarah kodifikasi Hadits-- berlangsung hingga masa khalifah Umar bin Abdul Azis . Disamping itu, karena seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya persoalan hidup dari berbagai aspek kehidupan manusia, maka sahabat dan ulama mengambil langkah ijtihad untuk mencari makna ayat-ayat al-Qur'an, bila mereka tidak menemukan nash-nash di dalam al-Qur'an dan Hadits. Termasuk dalam hal ini, ijtihad dalam menafsirkan al-Qur'an yang dikenal dengan istilah al-tafsir bi al-dirayah atau al-tafsir bi al-ra'yi .
Al-Qur'an sebagai tibyan (penjelasan) tidak menafsirkan setiap kata, kalimat dan ayat-ayatnya secara menyeluruh melainkan hanya sebatas kata atau kalimat yang dipandang sulit untuk dipahami oleh manusia. Oleh karena itu dalam kerangka tujuan realistik dan idealistik, al-Qur'an perlu ditafsirkan ayat-ayatnya secara benar sesuai dengan makna yang sesungguhnya atau makna yang mendekati kebenaran yang dikehendaki ayat-ayat itu sendiri. Itulah sebabnya Rasulullah Saw, memberikan tafsiran terhadap ayat-ayat yang turun bila diperlukan penjelasan. Langkah seperti ini sesungguhnya diikuti oleh para sahabatnya, tabiin dan para ulama sepanjang zaman.
Adapun tujuan ilmu tafsir, menurut Muhammad Abduh, adalah merealisasikan keberadaan al-Qur’an itu sendiri sebagai petunjuk dan rahmat Allah, dengan menjelaskan hikmah dibalik makna yang terkandung di dalam ayat-ayatnya untuk mencari kebenaran atau mendekati kebenaran makna yang dikendaki oleh al-Qur’an itu sendiri . Tujuan ini dikembangkan oleh Amin al-Khulli yang menyatakan bahwa tujuan ilmu tafsir adalah melakukan kontemplasi terhadap ayat-ayat al-Qur’an sebagai Kitab bahasa Arab yang Maha Agung dan mempunyai dampak kesusastraan yang paling besar (Kitab al-Arabiyyah al-Akbar) . Selanjutnya al-Qur’an menurutnya adalah Kitab yang melanggengkan bahasa Arab dari kehancurannya, dan menjadikannya kriterium dalam penelitian tata bahasa dan sastra. Sehingga dengan demikian, pengkajian tafsir dari aspek bahasa dan sastra dalam al-Qur`an merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum melangkah penafsirannya lebih jauh ke tujuan selanjutnya . Kalau tidak demikian, menurut al-khulli, siapa pun yang melakukan penafsiran al-Qur`an tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Jadi penafsiran kontemporer, menurutnya, adalah interpretasi bahasa dan sastra yang didasarkan atas metodologi yang tepat, kelengkapan berbagai aspek, dan kesinkronan distribusi pembahasan .
Sejalan dengan ini, sebagaimana diketahui bahwa al-Qur'an banyak mengungkap kata "thaghut" dalam berbagai surah atau ayat-ayatnya. Namun tidak ada satupun ayat al-Qur'an yang menafsirkan atau menginterpretasikan makna thaghut secara rinci dan konkrit. Demikian pula kitab-kitab turats (kitab-kitab tafsir klasik) belum menyentuh penafsirannya pada tataran relitas kehidupan manusia di era globalisasi sekarang ini. Oleh sebab itu berangkat dari sinilah, maka dibutuhkan penafsiran atau interpretasi tentang thaghut melalui pendekatan hermeneutik dengan metode maudhui` untuk mengungkap makna tekstual , makna kontekstual, dan makna relevan dibalik kata itu.
Dalam kitab Mu'jam al-Mufahras li Al-fâzh al-Qur'an, ditemukan bahwa kata "al-thaghut" didalam al-Qur'an terdapat pada 5 surah, dalam 8 ayat. Akan tetapi dengan beragam derivasinya tersebar pada 27 surat, dalam 39 ayat . Kata thaghut adalah lafazh yang terdapat didalam al-Qur'an, yang diulang sebanyak delapan kali. Namun dalam tataran realitas kehidupan manusia, terutama umat Islam yang mengimani al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman hidupnya, belum banyak mengenal istilah ini, dan bahkan boleh jadi tidak sedikit diantara mereka belum pernah mendengar istilah ini. Kalau mendengar saja belum pernah, apalagi memahaminya. Oleh sebab itu, menurut penulis kata ini sebaiknya dipopulerkan dan disosialisasikan pengertian dan penafsirannya kepada masyarakat Islam, sehingga mereka tidak terjebak masuk kedalam lingkaran thaghut, atau paling tidak mereka dapat memahami makna thaghut yang dikehendaki oleh ayat-ayat al-Qur'an kemudian meninggalkan segala bentuk perbuatan, sifat-sifat dan karakternya.
B. Pengertian Thaghut
Secara etimologis (ilmu asal-usul kata) dan secara leksikal (berhubungan dengan kamus), kata thaghut (طاغوت) dalam Kamus al-Munjid,
berasal dari kata-kata: طغى يطغو طغوا وطغوا وطغوانا: artinya: جاوز القدر والحـد. (melampaui ukuran dan batas), dan kata thaghut artinya adalah setiap pangkal kesesatan, setan yang mengeluarkan dari jalan kebenaran, dan setiap sesembahan selain Allah. Al-thawaghi dan al-thawaghit adalah rumah-rumah berhala. Sedangkan dalam Kamus al-Munawwir, thaghut berasal dari akar kata: طغى يطغى طغيا و طغيانا, artinya: melampauai batas. Bisa juga dari akar kata: طغى يطغو طغوا وطغوا وطغوانا, artinya: melampaui ukuran dan batas. Sedangkan kata thaghut (طاغوت) artinya adalah berhala, setan, patung, dukun dan setiap yang disembah selain Allah Ta'ala .
Sedangkan kata thaghut dalam kamus Lisan al-Arab, menyatakan bahwa kata thaghut bisa dalam konteks tunggal dan jamak atau bisa menjadi muzakkar dan mua'nnats. Thaghut wazan-nya (timbangannya) sama dengan kata fa'aluut (فعلوت), maka disebut thaghayut (طغيوت), kemudian posisi Ya (ي) didahulukan sebelum ghain (غ) dalam keadaan berharakat fathah, dan sebelumnya juga fathah, maka jadilah thayaghut طيغوت)), lalu huruf Ya dibalik menjadi huruf alif, maka jadilah thaghut (طاغوت) jamaknya: طواغيت و طواغ : , كل مجاوز حـده فى معصـيةِ artinya: setiap yang melampaui batas dalam kemaksiatan. Hal yang hampir senada dengan penjelasan kata thaghut diatas, juga dikemukakan dalam kitab Musykilah I'rab al-Qur'an, bahwa kata thaghut (طاغوت) adalah isim musytaq dari tagha (طغى) , yang dibalik (dimodifikasi), asalnya adalah thaghayut (طغيوت) berwazan dengan fa'alut (فعلوت) seperti jabarutجبروت) ), huruf ya (ي) dibalik pada posisi ghain (غ) maka jadilah thayaghut(طيغوت) , kemudian ya dibalik lagi menjadi alif karena berharakat dan sebelumnya fathah maka jadilah thaghut(طاغوت) .
Selain dari pada itu, makna thaghut menurut John L. Esposito, dalam Insiklopedinya menyatakan bahwa: "terma thaghut, dari akar taghy ("memberontak, melanggar, atau melampaui batas"), disebut 8 kali dalam al-Qur'an, thaghut menunjukkan fokus persembahannya selain Allah, dan sering juga disebut sebagai "berhala" atau "setan", bahkan maknanya lebih luas dari pada itu" . Statement ini nampaknya cenderung mengklaim secara parsial bahwa makna thaghut hanya terfokus pada masalah teologis yang mengarah kepada persoalan peribadatan atau persembahan selain Allah.
Secara terminologis, kontekstualitas pengertian thaghut dalam tafsir al-Qur'an, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Thabari dalam kitabnya, adalah "sesuatu yang melampaui batas syariat Allah lalu disembah selain-Nya, baik dengan cara dipaksa maupun karena taat kepadanya, yang berupa manusia, setan, berhala, atau bentuk ciptaan lain" . Pengertian ini hampir sama dengan pengertian yang diungkapkan oleh John L. Esposito sebagai dikutip dari pernyataan Abu al-A'la al-Maududi yang mendifinisikan thaghut dalam tafsirnya sebagai "segala sesuatu yang melampaui batas garis yang telah ditetapkan dan merebut kekuasaan ketuhanan—bukan hanya kufur kepada Allah, tetapi juga telah memaksakan kehendaknya diatas iradah (kehendak) Allah" . Bila dicermati pengertian thaghut yang diberikan al-Thabari dan Abu al-A'la al-Maududi, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa stressing penafsiran keduanya tentang makna thaghut adalah mengarah secara parsial kepada pemahaman teologis dalam bentuk peribadatan atau bentuk penyembahan selain Allah.
Terma thaghut (طاغوت) merupakan istilah yang diungkapkan berkali-kali di dalam ayat-ayat al-Qur'an. Dalam al-Qur'an, pengertian thaghut dapat diketahui maknanya melalui tafsir yang sesuai dengan redaksi ayat-ayat yang memuat kata tersebut. Kata thaghut di dalam al-Qur'an disebutkan delapan kali di dalam 5 (lima) surah dan 8 (delapan) ayat. Masing-masing ayat memiliki makna penafsiran tekstual dan kontekstual yang beragam. Pengertian thaghut dalam surah al-Baqarah ayat 256, berarti setan , dalam surah yang sama pada ayat 257, Mujahid berkata: thaghut adalah setan dalam bentuk manusia . Pada surah al-Nisa ayat 51, thaghut berarti; tukang sihir dan dukun , dalam surah yang sama pada ayat 60, thaghut bermakna Ka'ab bin al-Asyraf seorang hakim Yahudi , pada ayat 76 dalam surah yang sama, thaghut maknanya adalah ketaatan terhadap setan . Pada surah al-Maidah ayat 60, thaghut diartikan sebagai segala sesuatu yang melampaui batas ketentuan Allah . Pada surah al-Nahl ayat 36, kata thaghut artinya adalah setiap sesuatu yang mengajak kepada kesesatan . Pada surah al-Zumar ayat 17, thaghut diartikan sebagai sesuatu yang disembah selain Allah Swt .
Deskripsi makna thaghut sebagaimana yang telah dijelaskan secara etimologis dan leksiologis oleh pakar ahli bahasa di dalam kamusnya masing-masing di atas, menurut penulis dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa secara tekstual tafsir pengertian thaghut adalah setiap perbuatan melampaui batas. Bila pengertian ini ditakhsiskan berdasarkan makna ta'wil , maka dapat disebut maknanya sebagai; setan, dukun, tukang sihir, atau berhala. Ta'wil makna tekstual seperti ini sesungguhnya telah ditafsirkan oleh para ahli tafsir klasik terdahulu. Pengertian makna seperti inilah yang banyak diungkapkan dalam kitab-kitab tafsir yang beraliran pemahaman tafsir bi al-ma'tsur. Kemudian pengertian tekstual ini terus berkembang dari masa ke masa sehingga para pakar tafsir kontemporer menginterpretasikan maknanya secara kontekstual yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.
C. Asbab al-Nuzul
Imam al-Wahidi berpendapat bahwa untuk mengetahui tafsir suatu ayat al-Qur’an, tidak mungkin tanpa mengetahui latar belakang peristiwanya dan kejadian turunnya . Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mengertahui asbab nuzul ayat, membantu dalam memahami makna ayat, karena mengetahui kejadian turunnya itu memberikan dasar untuk mengetahui penyebabnya . Dari ungkapan al-Wahidi dan Ibnu Taimiyah ini memberikan aba aba kepada setiap orang yang bermaksud menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an, agar tidak melupakan asbab al-nuzul, karena hal itu sangat membantu dalam pemahaman ayat secara benar dan komprehensif. Walaupun sesungguhnya ayat-ayat al-Qur’an secara keseluruhan tidak turun melalui asbab al-nuzul, namun dalam hal-hal tertentu tidak sedikit ayat-ayatnya yang turun melalui berbagai peristiwa atau kejadian. Misalnya ayat-ayat tentang thaghut, dari delapan ayat yang berbicara tentang kata thaghut, hanya 5 ayat yang memiliki sebab-sebab turunnya.
Kata thaghut yang terdapat pada ayat 256 surah al-Baqarah, sesungguhnya asbab nuzulnya terdapat dalam riwayat Ibnu Abbas bahwa sebelum Islam datang, ada seorang wanita yang selalu kematian anaknya. Ia berjanji kepada dirinya, apabila ia mempunyai anak dan hidup akan dijadikan Yahudi. Ketika Islam datang dan Kaum Yahudi Bani Nadhir diusir dari Madinah (karena pengkhianatannya), ternyata anak tersebut dan beberapa anak lainnya yang sudah termasuk keluarga Anshar, terdapat bersama-sama kaum Yahudi. Berkatalah kaum Anshar: “Jangan kita biarkan anak-anak kita bersama mereka (Yahudi)” . Maka turunlah ayat 256 al-Baqarah sebagai teguran bahwa tidak ada paksaan dalam Islam.
Sedangkan ayat 257 surah al-Baqarah, sebab nuzulnya ayat adalah bersumber dari riwayat yang mengemukakan bahwa ayat ini ditujukan kepada kaum yang beriman kepada Isa dan yang tidak beriman kepadanya. Setelah Muhammad Saw diutus, ada yang beriman kepada Isa dan ada juga yang kufur kepada Muhammad Saw, dan ada yang kufur kepada Isa, tapi ada juga yang beriman kepada nabi Muhammad saw .
Menurut al-Wahidi, surah al-Nisa ayat 51, turun disebabkan adanya suatu peristiwa yang terjadi setelah perang Uhud. Kaab bin al-Asyraf (orang Yahudi) datang dengan 70 pasukan berkudanya ke Mekkah untuk membatalkan perjanjian antara mereka dengan Rasulullah Saw. Kemudian Ka’ab menemui Abi Sofyan dan orang-orang Quraish: Lalu Orang-orang Quraish berkata: Kalian adalah Ahli Kitab, dan Muhammad pemilik Kitab. Kami telah aman dengan perjanjian yang penuh dengan penipuan, kalau kalian mau bersama kami, maka bersujudlah kepada dua berhala ini . Maka turulah ayat ini.
Menurut Rasyid Ridha, bahwa ayat 60 surah al-Nisa turun disebabkan oleh seorang Yahudi berselisih dengan seorang munafiq. Yahudi itu mengusulkan untuk meminta bantuan kepada Nabi dalam menyelesaikan perselisihan itu karena ia tahu bahwa Nabi tidak akan mau menerima risywah (sogokan), tetapi mereka juga sepakat untuk meminta bantuan kepada seorang pendeta di juhainah. Maka turunlah ayat ini sebagai cercaan terhadap perbuatan munafiq itu . Sedangkan menurut al-Zamakhsyari, bahwa ayat ini turun berdasarkan riwayat bahwa seorang munafiq berselisih dengan seorang Yahudi, lalu Yahudi itu mengajak menghadap kepada Rasulullah, namun munafiq itu justeru mengajak menghadap kepada Ka’ab bin al-Asyraf. Kemudian keduanya bertahkim kepada Rasulullah Saw, Yahudi itu menerimanya namun munafiq itu tidak menerimanya, lalu berkata: Mari kita berhakim kepada Umar bin Khattab, Orang Yahudi itu berkata kepada Umar: Rasulullah telah memutuskan perkara kami tetapi dia (orang munafiq itu) tidak rela dengan keputusannya, lalu Umar berkata kepada munafiq itu: apa itu benar? Dia menjawab: ya benar. Maka Umar berkata: tunggu sampai saya keluar, lalu umar masuk kesuatu tempat kemudian keluar dengan sebilah pisau lalu menebas leher munafiq tersebut dan berkata: demikianlah hukum bagi orang yang tidak menerima hukum dari Allah dan Rasulullah saw .
Adapun sebab turunnya surah al-Zumar ayat 17, dalam suatu riwayat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "الذين اجتنبوا الطاغوت" dalam ayat ini ialah Zaid bin ‘Amr bin Nafil, Abu Dzar al-Ghifari dan Salman al-Farisi di zaman Jahiliah telah mengaku bahwa “tiada Tuhan kecuali Allah” . Imam al-Wahidi berpendapat bahwa untuk mengetahui tafsir suatu ayat al-Qur’an, tidak mungkin tanpa mengetahui latar belakang peristiwanya dan kejadian turunnya . Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mengertahui asbab nuzul ayat, membantu dalam memahami makna ayat, karena mengetahui kejadian turunnya itu memberikan dasar untuk mengetahui penyebabnya . Dari ungkapan al-Wahidi dan Ibnu Taimiyah ini memberikan aba aba kepada setiap orang yang bermaksud menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an, agar tidak melupakan asbab al-nuzul, karena hal itu sangat membantu dalam pemahaman ayat secara benar dan komprehensif. Walaupun sesungguhnya ayat-ayat al-Qur’an secara keseluruhan tidak turun melalui asbab al-nuzul, namun dalam hal-hal tertentu tidak sedikit ayat-ayatnya yang turun melalui berbagai peristiwa atau kejadian. Misalnya ayat-ayat tentang thaghut, dari delapan ayat yang berbicara tentang kata thaghut, hanya 5 ayat yang memiliki sebab-sebab turunnya.
Kata thaghut yang terdapat pada ayat 256 surah al-Baqarah, sesungguhnya asbab nuzulnya terdapat dalam riwayat Ibnu Abbas bahwa sebelum Islam datang, ada seorang wanita yang selalu kematian anaknya. Ia berjanji kepada dirinya, apabila ia mempunyai anak dan hidup akan dijadikan Yahudi. Ketika Islam datang dan Kaum Yahudi Bani Nadhir diusir dari Madinah (karena pengkhianatannya), ternyata anak tersebut dan beberapa anak lainnya yang sudah termasuk keluarga Anshar, terdapat bersama-sama kaum Yahudi. Berkatalah kaum Anshar: “Jangan kita biarkan anak-anak kita bersama mereka (Yahudi)” . Maka turunlah ayat 256 al-Baqarah sebagai teguran bahwa tidak ada paksaan dalam Islam.
Sedangkan ayat 257 surah al-Baqarah, sebab nuzulnya ayat adalah bersumber dari riwayat yang mengemukakan bahwa ayat ini ditujukan kepada kaum yang beriman kepada Isa dan yang tidak beriman kepadanya. Setelah Muhammad Saw diutus, ada yang beriman kepada Isa dan ada juga yang kufur kepada Muhammad Saw, dan ada yang kufur kepada Isa, tapi ada juga yang beriman kepada nabi Muhammad saw .
Menurut al-Wahidi, surah al-Nisa ayat 51, turun disebabkan adanya suatu peristiwa yang terjadi setelah perang Uhud. Kaab bin al-Asyraf (orang Yahudi) datang dengan 70 pasukan berkudanya ke Mekkah untuk membatalkan perjanjian antara mereka dengan Rasulullah Saw. Kemudian Ka’ab menemui Abi Sofyan dan orang-orang Quraish: Lalu Orang-orang Quraish berkata: Kalian adalah Ahli Kitab, dan Muhammad pemilik Kitab. Kami telah aman dengan perjanjian yang penuh dengan penipuan, kalau kalian mau bersama kami, maka bersujudlah kepada dua berhala ini . Maka turulah ayat ini.
Menurut Rasyid Ridha, bahwa ayat 60 surah al-Nisa turun disebabkan oleh seorang Yahudi berselisih dengan seorang munafiq. Yahudi itu mengusulkan untuk meminta bantuan kepada Nabi dalam menyelesaikan perselisihan itu karena ia tahu bahwa Nabi tidak akan mau menerima risywah (sogokan), tetapi mereka juga sepakat untuk meminta bantuan kepada seorang pendeta di juhainah. Maka turunlah ayat ini sebagai cercaan terhadap perbuatan munafiq itu . Sedangkan menurut al-Zamakhsyari, bahwa ayat ini turun berdasarkan riwayat bahwa seorang munafiq berselisih dengan seorang Yahudi, lalu Yahudi itu mengajak menghadap kepada Rasulullah, namun munafiq itu justeru mengajak menghadap kepada Ka’ab bin al-Asyraf. Kemudian keduanya bertahkim kepada Rasulullah Saw, Yahudi itu menerimanya namun munafiq itu tidak menerimanya, lalu berkata: Mari kita berhakim kepada Umar bin Khattab, Orang Yahudi itu berkata kepada Umar: Rasulullah telah memutuskan perkara kami tetapi dia (orang munafiq itu) tidak rela dengan keputusannya, lalu Umar berkata kepada munafiq itu: apa itu benar? Dia menjawab: ya benar. Maka Umar berkata: tunggu sampai saya keluar, lalu umar masuk kesuatu tempat kemudian keluar dengan sebilah pisau lalu menebas leher munafiq tersebut dan berkata: demikianlah hukum bagi orang yang tidak menerima hukum dari Allah dan Rasulullah saw .
D. Tafsir Makna Thaghut
Banyaknya lafazh thaghut dan derivasinya yang terdapat dalam kadungan ayat-ayat al-Qur'an, maka konsekwensinya berakibat pada munculnya perbedaan persepsi di kalangan ulama tafsir dalam memahami, memaknai dan menginterpretasikan kata thaghut. Misalnya, kata al-Thaghut dalam surah al-Baqarah ayat 256 yang berfirman: )...فمن يكفربالطاغـوت......maka barangsiapa yang inkar kepada thaghut…) . Ayat ini mengundang perbedaan persepsi dan penafsiran dalam memahaminya. Banyak kitab-kitab tafsir yang bernuasa tafsir bi al-Ma'tsur atau tafsir bi al-dirayah menarik ayat ini kedalam persoalan teologis, dan memberikan penafsiran yang berbeda. Antara lain; Abu Ja'far al-Thabari (224H–310H) dalam kitab tafsirnya mengemukakan bahwa makna thaghut adalah sesuatu yang melampaui batas syariat, lalu disembah selain Allah, baik dengan cara dipaksa maupun karena taat kepadanya, yang berupa manusia, setan, berhala, atau bentuk ciptaan lain. Kemudian dalam penafsirannya, dia mengklasifikasikan makna thaghut dalam tiga kategori dengan merujuk pada riwayat-riwayat para sahabat, yaitu; setan, sihir dan dukun . Klasifikasi yang identik dengan ini, juga dikemukakan oleh Ibn Katsir (700 H/1300 M-774 H/1373 M) dalam kitabnya yang memaknai thaghut dengan merujuk kepada riwayat-riwayat para sahabat dan tabiin . Kelihatannya Ibn Katsir dalam menafsirkan kata thaghut cenderung mengklasifikasikan thaghut dalam tiga bentuk wujudnya yaitu; 1) dukun, 2) setan dalam bentuk manusia, dan 3) sesuatu yang disembah selain Allah. Hal yang senada dengan klasifikasi yang diberikan Ibn Katsir ini, juga diikuti oleh Jalal al-Din al-Sayuti dalam kitabnya , yang memuat riwayat-riwayat tentang thaghut. Hanya saja al-Sayuti menambahkannya riwayat dari Ibn Jarir dari Abi al-Aliyah, berkata: al-thaghut adalah tukang sihir, dan juga riwayat dari Umar bin Khattab berkata: al-thaghut adalah setan. Kelasifikasi ini kelihatannya juga diikuti oleh Mushtafa al-Hushan al-Mansuri dalam kitabnya yang menguraikan bahwa makna thaghut adalah setan, berhala dan setiap sesuatu yang disembah selain Allah.
Lain halnya dengan al-Qurtubi (w. 671 H) dalam kitab tafsirnya yang memaknai thaghut sebagai segala bentuk sembahan selain Allah, kemudian ia mengklasifikasikannya dalam empat kategori, yaitu: 1) Setan, 2) dukun, 3) berhala, dan 4) setiap yang mengajak kepada kesesatan. Seirama dengan klasifikasi ini agaknya diikuti oleh Abd al-Rahman ibn Nashir al-Sa'dy (1307 H – 1376 H) dalam kitabnya yang mengklasifikasikan makna thaghut kedalam empat kategor. 1) Sihir 2) Dukun 3) Sembahan selain Allah 4) Ketaatan pada setan. Sedangkan al-Fakhru al-Razi dalam kitabnya berpendapat bahwa selain empat kategori di atas, dia menambahkan bahwa makna thaghut adalah bentuk kedurhakaan jin dan manusia yang melampaui batas ketika berhubungan dengan sesuatu. Lalu menjadikan sesuatu ini penyebab kesesatan. Demikian pula penafsiran yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, yang berpendapat bahwa selain empat kategori di atas, dia juga menambahkan bahwa thaghut adalah kedurhakaan ahli kitab .
Beda pula dengan penafsiran yang dikemukakan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziah, sebagai dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa thaghut adalah apapun yang dilakukan manusia melampaui batas ketentuan, baik berupa sesembahan, taqlid ataupun bentuk ketaatan. Dia juga berkata: thawaghit (jama' thaghut) banyak ragamnya, namun sumbernya ada lima: Pertama, Iblis yang dilaknat Allah. Kedua, Orang yang disembah sedang ia rela. Ketiga, Orang yang mengajak manusia menyembah dirinya. Keempat, Orang yang mengaku mengetahui hal-hal ghaib. Kelima, Orang yang menghukum selain apa diwahyukan Allah. Kemudian Wahbah al-Zuhaili sendiri mengomentari pendapat Ibn al-Qayyim al-Jauziah, bahwa thaghut sesungguhnya adalah orang yang tidak kuasa mengendalikan diri terhadap persembahan batil yang melampaui batas, agar iman di dalam hati terlepas, dan bisikan nafsu syahwat terlena, seperti ambisi kekuasaan dan kekayaan atau gemar berbuat kekejian, kemungkaran, dan kezaliman . Sedangkan menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi, thaghut adalah sesuatu yang disembah dan diyakininya sebagai penyebab perbuatan melampaui batas, atau keluar dari kebenaran lantaran menyembah makhluk, baik berupa manusia, tempat sesajian, berhala, taqlid pemimpin atau hawa nafsu . Penafsiran ini agaknya sama dengan penafsiran yang diungkapkan oleh Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh dalam kitab tafsir al-Manar Hal yang senada dengan ini, Syeikh Muhammad bin Abd. Al-Wahhab didalam risalah Ma'na al-Thaghut wa Ruusu Anwa'ihi, berpendapat bahwa tafsir makna thaghut bersifat umum, yaitu; segala sesuatu yang disembah selain Allah, dan dia rela disembah, diikuti dan ditaati diluar ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya, maka ia adalah thaghut. Kemudian dia mengklasifikasikan thaghut itu kedalam lima kategori, yaitu; 1). Setan yang mengajak beribadah selain kepada Allah. 2). Penguasa dzalim yang mengubah hukum-hukum Allah. 3). Hakim yang memutuskan perkara hukum selain apa yang disyariatkan Allah. 4). Orang yang mengaku mengetahui hal-hal ghaib. 5). Orang yang disembah selain Allah dan ia rela . Kelihatan tafsir terakhir ini cenderung mengarah kepada makna kontekstual tentang thaghut.
Dari beberapa pendapat di atas, terlihat adanya perbedaan pendapat yang signifikan di kalangan ulama dalam memahami, menafsirkan dan menginterpretasikan serta mengklasifikan kata thaghut. Sungguhpun para ulama telah membuat klasifikasi makna thaghut, bukan berarti persoalan terma ini telah ditafsirkan secara komprehensif dan tuntas. Dalam arti, masih terdapat celah-celah yang memungkinkan makna thaghut ini untuk dikaji, ditafsirkan dan diinterpretasikan kembali. Lebih-lebih bila makna thaghut dipahami sebagai lafazh yang mengandung makna umum sebagaimana kaedah tafsir yang berbunyi : العبـرة بعموم الألفاظ لا بخصـوص الأسـباب (Pemahaman lafazh suatu ayat karena redaksinya yang bersifat umum, bukan karena sebab turunnya yang bersifat khusus) . Oleh sebab itu, adanya keragaman klasifikasi thaghut yang dikemukakan oleh para ulama tafsir merupakan bukti adanya celah-celah yang masih membutuhkan penafsiran atau interpretasi yang lebih luas, jelas dan konkrit. Sebagai contoh, tafsir makna thaghut yang dikemukakan oleh al-Thabari, Ibnu Katsir dan Al-Sayuthi yang notabene tafsir bi al-ma'tsur masih menyisakan pertanyaan “apakah masih ada thaghut selain setan, dukun, tukang sihir, berhala dan setiap yang disembah selain Allah?". Lain pula halnya makna thaghut yang ditawarkan al-Qurtubi, Fakhr al-Razi dan Ibnu Taimiyah . Kelihatannya masih mengundang pertanyaan, "bagaimana sistim kinerja thaghut dalam mempengaruhi manusia sehingga masuk dalam lingkarannya?". Demikian pula makna thaghut yang ditafsirkan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, Wahbah al-Zuhaili, Musthafa al-Maraghi, Syeikh Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Muhammad bin Abd. Al-Wahhab , kelihatannya sudah mencakup penafsirannya dari berbagai aspek kehidupan manusia. Namun demikian menurut penulis masih menimbulkan pertanyaan; apakah masih bisa makna thaghut itu dikembangkan maknanya secara komprehensif, sehingga makna tekstual, kontekstual, dan relevansinya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman?, dan satu pertanyaan mendasar terhadap keragaman makna thaghut yang dikemukakan oleh para ulama tersebut yaitu; apakah kontekstualitas makna thaghut masih bisa diteliti sehingga maknanya menyentuh pada kompleksitas kehidupan manusia?. Kalaupun jawabannya “Ya”, maka masih ada tersisa pertanyaan realitis, yaitu apakah selain makna yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir klasik maupunkontemporer masih dapat dikembangkan interpretasi maknanya sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan kehidupan manusia di zaman sekarang ini?.
Bila diteliti secara cermat tingkat keragaman persepsi para ulama tafsir dalam memaknai thaghut, maka setidaknya dari penafsiran mereka itu tercermin makna esensial dan subtansial. Walaupun secara esensial tidak banyak orang yang berani dan dapat menjelaskan interpretasinya secara defenitif dan integral melalui pendekatan hermeneutik dengan menggunakan metode maudhu`i. Sedangkan secara subtansial makna thaghut dapat dipahami dan ditakhsiskan penafsirannya pada hal-hal yang lebih spesifik. Misalnya thaghut di satu sisi dapat dipahami maknanya sebagai supranatural (ghaib) seperti; setan, iblis dan sejenisnya. Di sisi lain juga bisa bermakna natural (konkrit) seperti; berhala, patung dan bentuk manusia. Dikatakan setan sebagai thaghut karena sifat-sifatnya yang cenderung melampaui batas syariat Allah, dan mengeluarkan manusia dari cahaya iman kepada kegelapan (kesesatan). Dikatakan berhala atau patung sebagai thaghut karena merupakan tempat sesajian setan yang dipergunakan manusia untuk menyembah selain Allah. Dikatakan manusia sebagai thaghut karena apa yang dilakukan dalam prakteknya bersumber dari perbuatan setan yang cenderung menyesatkan manusia dari kebenaran kepada kebatilan. Seadainya makna thaghut ditafsirkan seperti assumsi ini, maka penafsirannya mengerucut kepada pengertian yang parsial, yaitu terbatas pada persoalan teologis . Pada hal penulis dalam penelitian ini, bertujuan untuk mendalami, mengembangkan, dan memperluas makna thaghut hingga sampai pada tataran makna literal (tekstual), makna konteks (kontekstual) dan makna relevan (relevansinya dengan realitas kehidupan manusia).
Berpijak dari statemen di atas, maka objektifitas makna thaghut dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penafsirannya pada interpretasi literal (teks dan konteks) melalui kajian etimologis dan terminologis yang mengarah kepada makna leksikal, gramatikal dan historis. Sedangkan subjektifitas makna thaghut dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penafsirannya pada interpretasi monistik (makna tunggal) dan interpretasi pluralistik (makna banyak), yang mengarah pada makna relevansi dan sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi kekinian dari berbagai disiplin keilmuan.
Pada tataran realitas kehidupan manusia, sepanjang pengetahuan penulis bahwa ungkapan terma thaghut dikomunitas Islam Indonesia khususnya, belum tersosialisasi dan bahkan belum menjadi sebuah istilah yang populer terdengar. Kalaupun ada terdengar, itupun muncul sekali-kali dari pojok-pojok pesantren atau dari mulut intelektual muslim, ulama dan ustadz-ustadz saja. Hal ini terjadi, menurut asumsi penulis, disebabkan dua alternatif kemungkinan. Pertama, karena bisa saja terma ini agak sensitif dikalangan bangsa Indonesia yang dalam tanda kutip cenderung melakukan tindakan-tindakan thaghut, baik disengaja maupun tidak sengaja. Atau boleh jadi karena penafsiran makna thaghut ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat Islam, dan belum tersosialisasi di seluruh sektor pendidikan terutama di lembaga pendidikan Islam. Kurikiulum pendidikan agama yang diajarkan, dari sejak awal masuk madrasah atau sekolah dasar hingga di perguruan tinggi tidak pernah diajarkan ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang thaghut dengan berbagai bentuk, jenis, dan karakternya. Kedua, adalah penafsiran tentang ayat-ayat thaghut masih tersimpan di dalam kitab-kitab tafsir berbahasa Arab yang nota bene sangat sulit dipahami oleh komunitas muslim Indonesia, kecuali melalui alih bahasa kedalam bahasa Indonesia. Jika asumsi penulis di atas adalah benar, maka paradigma makna thaghut seyogyanya ditafsirkan berdasarkan makna tekstual atau kontekstual secara rinci, benar dan komprehensif, kemudian dieksposkan, dipublikasikan dan disosialisasikan diseluruh komunitas Islam melalui media cetak ataupun media elektronik agar mereka dapat memahaminya dengan benar. Dengan demikian mereka diharapkan dapat mengkufuri thaghut dan beriman kepada Allah.
Pada satu sisi, aktualisasi subjektifitas makna thaghut dalam al-Qur'an semakin menjadi urgen jika dikaitkan dengan perkembangan sosial kultural di era globalisasi dewasa ini yang dengan cara terang-terangan membawa pengaruh dampak negatif terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Aspek biologis misalnya, pengaruh thaghut sangat gencar mempengaruhi manusia agar melakukan pelanggaran asusila untuk memenuhi kebutuhan seksual. Dari aspek hukum, pengaruh thaghut sangat aktif menggerogoti pikiran para pakar hukum alias hakim dan pelindung-pelindungnya agar menyimpang dari hukum syari'at yang telah ditetapkan Allah Swt. Dari aspek kekuasaan, peran thaghut dalam mempengaruhi para penguasa dan pejabat tidak pernah menyerah agar mereka masuk dalam lingkarannya, sehingga mereka dengan mudah menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan-tindakan penyelewengan terhadap syari'at al-Qur'an. Dari aspek politik, bujukan thaghut terhadap para praktisi politik yang ambisius jabatan, semakin berpeluang mempengaruhi mereka agar melakukan berbagai macam cara yang sesat untuk mengejar tujuan tertentu. Demikian pula dari aspek ekonomi, pengaruh thaghut selalu mengajak pelaku ekonom, baik dalam skala makro maupun dalam skala mikro, agar tetap melakukan praktek riba dan penipuan dalam berbagai sistim prekonomian.
Di sisi lain, objektifitas makna thaghut sesungguhnya sudah tergambar dalam kitab-kitab tafsir, baik klasik maupun kontemporer, yang ditafsirkan melalui pendekatan tafsir bi al-ma`tsur dan tafsir bi al-ra`yi secara leksikal, semantik, dan historis. Sebagai diketahui bahwa kata thaghut di dalam al-Qur`an terpencar pada surah dan ayat yang berbeda. Hal ini memang harus diakui, sebab satu tema permasalahan dalam al-Qur`an, urutan ayat-ayat dan surahnya tidak disusun secara tematis. Tidak mengikuti sistimatika yang biasa ditulis manusia sebagai karya ilmiah. Al-Qur`an hanya memaparkan berbagai tema dalam satu bagian secara bersamaan, tidak berurutan dan kadang tidak berhubungan. Misalnya, dalam surah al-Baqarah, terdapat beragam ungkapan dan banyak rona yang mewarnai tema-tema yang berbeda, yang dijelaskan dan dilengkapi pada surah dan ayat yang lain. Namun semua itu, harus diyakini, pasti mempunyai tujuan dan hikmah dibalik itu, yang harus bisa diteliti secara ilmiah pada kajian-kajian yang memang membahas persoalan itu.
Penafsiran al-Qur`an yang mengikuti urutan ayat dan surahnya, tentu saja tidak akan memberikan pemahaman yang teliti dan pengetahuan yang benar terhadap makna dan tujuannya. Oleh sebab itu, tiada jalan lain, kecuali harus merujuk dan melengkapi penafsiran ayat al-Qur`an dengan ayat lain yang mempunyai tema senada, sehingga dengan demikian tidak terjebak dalam pemahaman parsial.
Merujuk dari assumsi inilah, maka sangat diperlukan pemahaman yang benar dan komprehensif tentang makna thaghut, melalui pendekatan hermeneutik dengan metode maudhu`i sebagai acuan kerangka berfikir dalam penafsiran al-Qur`an. Kemudian diharapkan ini dapat memberikan penyegaran makna thaghut sesuai dengan makna yang dikehendaki al-Qur’an atau paling tidak mendekati kebenaran yang dikehendaki al-Qur’an.
E. Kesimpulan
Bertitik tolak dari uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa objektifitas penafsiran makna thaghut sesungguhnya sudah tergambar dalam kitab-kitab tafsir, baik klasik maupun kontemporer, yang ditafsirkan melalui pendekatan tafsir bi al-ma`tsur dan tafsir bi al-ra`yi secara leksikal, semantik, dan historis. Jadi makna objektifitas kata thaghut adalah sesuatu yang melampaui batas ketentuan Allah Swt. Dalam tafsir dikatakan bahwa thaghut adalah setan, berhala, dukun, tukang dan setan dalam bentuk manusia. Sedangkan makna subjektifitas kata thaghut adalah segala bentuk sikap, prilaku, mental dan karakter yang ada pada manusia yang cenderung melanggar dan melampauai batas-batas syari`at yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Misalnya; penguasa zhalim, hakim zhalim, pengguna miras (ganja, narkoba dan sejenisnya), pemakan riba, pelaku zina, dan lain-lainnya yang terus menerus melakukan perbuatan maksiat dan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan syari`at Islam.
PENULIS : DRS. ABD. GHAFFAR. MA
(DOSEN IAIN STS. JAMBI)
DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA
Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya
Al-Alusi, Mahmud, Ruh al-Ma'ni fi Tafsir al-Qur'an al-Adzim wa al-Sab'i al- Matsani, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001., cet. I.
Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhri, Kairo: Dar al-Hadits, 2004.
Abd al-Wahhab, Muhammad, Risalah Ma'na Thaghut wa Ruusu Anwa'ihi dalam kitab Majmu' al-Tauhid, Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t,th.
Abu al-Abbas, Abd al-Halim bin Taimiyah, Daqaiq al-Tafsir al-Jami' li Tafsir Ibn Taimiyah, Damaskus: Muassasah Ulum al-Qur'an, 1404 H.
Al-Baqi, Fuad Abd, al-Mu'jam al-Mufahras li al-fâzh al-Qur'ân, Bairut: Dâr al-Ma'rifah, 1994, Cet. IV.
Al-Dzahabî, Muhammad Husain, al-Tafsîr wa al-Mufassirûn, Kairo, Maktabah al-Wahbah, 2000, cet. VII.
Al-Farmâwî, Muhammad Hijâzî, al-Bidâyah fî al-Tafsîr al-Maudhû'î, Mesir: Maktabat al-Jumhûriyyat, 1979
Ibnu Arabi (468-543H), Abi Bakar Muhammad Abdullah, Ahkam al-Qur'an li Ibn al-Arabi, Bairut: Dar al-Jil, 1987
Ibnu Katsir, Abu al-Fida' Ismail, Tafsir al-Qur'an al-Adzim (Tafsir Ibnu Katsir), Kairo: Dar al-Hadits, 1993, cet. VII.
Ibnu Taimiah, Taqiy al-Din, al-Tafsir al-Kabir li Ibn Taimiyah (Tafsir Ibnu Taimiyah), Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
Ithr, Nur al-Din, Manhaj al-Naqd Fi Ulum al-Hadits, Bairut: Dar al-Fikr, 1398, cet. III., h. 27
John. L. Esposito, The Oxford Encyclopedia of the modern Islamic World, (New York: Oxord University Press, 1995), vol 4. John. L. Esposito, The Oxford Encyclopedia of the modern Islamic World, (New York: Oxord University Press, 1995), vol 4.
Al-Mansuri, Mushtafa al-Hushan, Al-Muqtathif Min Uyun al-Tafsir, Damaskus: Dar al-Qalam, 1996, cet. I
Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, Tafsir al-Maraghi, Kairo: Daar al-Fikr, 2006
Al-Nasafi, Ahmad bin Mahmud, Tafsir al-Nasafi yang dikenal dengan Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Ta'wil, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001, cet. I.
Al-Qardhawi, Yusuf, “Metode Memahami al-Sunnah dengan Benar”. Judul asli “Kaifa Nata’ammal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah Ma’alim wa Dhawabith”. Pent. Saifullah Kamali, (Jakarta: Media Dakwah, 1994,)
Al-Qasimi,Muhammad Jamal al-Din, Tafsir al-Qasimi yang dikenal dengan kitab Mahasin al-Ta'wil
Qaththan, Manna', Mabahits fi Ulum al-Qur'an, Riadh: Mansyurat al-'Ashr al-Hadits, t.th, cet. III.,
Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad al-Anshari, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Kairo: Dar al-Hadits, t,th, cet. II
Quthub, Sayyid, Tafsir fi dzilal al-Qur'an, Kairo: Daar al-Syuruq, 2004
al-Razi, Fakhr al-Din, Tafsir al-Fakhr al-Razi (al-Tafsir al-Kabir wa Mafatiih al-Ghaib), Bairut: Dar al-Fikr, 2005, cet. I.
Ridha,Muhammad Rasyid, Tafsir al-Manar, Bairut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. I., 1999
Al-Sa'dy, Abd al-Rahman bin Nashir, Taisir al-Karim al-Rahman, Bairut: Muassasah al-Risalah, 1998.
Al-Sattar, Abd, Al-Madkhal fi al-Tafsir al-Maudhu'i, Kairo: Dar al-Thabaah wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1986, cet I,
Al-Sa'di, Abd al-Rahman bin Nashir, al-Qawaid al-Hisan li Tafsir al-Qur'an, Kairo: Maktabah al-Ma'arif, t,th,.
Al-Shabuni, Muhammad Ali, al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an, Bairut: Alam al-Kutub, 1985, cet. I
Al-Sayuthi, Jalal al-Din abd al-Rahman Abi Bakar, al-Dur al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004, cet. II
Al-Sayuthi, Jalal al-Din abd al-Rahman Abi Bakar, al-Itqa fi Ulum al-Qur’an, Bairut: Dar al-Fikr, t,th, jilid I,.
Al-Syatibi, Abu Ishak, al-Muwafaqat, Bairut: Dar al-Maa'rif, 1975, cet. II.
Syarif, M.M, A History of Muslim philosophy, Delhi, Santosh offset, 1995, vol.II, cet. IV.
Shihab, M. Quraish ,Tafsir al-Misbah,
Shihab, M. Qurais, Membumikan Al-Qur’an, Bandung: Mizan, 1994, cet VI
Al-Thabari, Abu Ja'far, Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an, Bairut: Dar al-Fikr, 1405 H.,
Al-Zamakhsyari (467-538H), Mahmud bin Umar bin Muhammad, al-Kasysyaf A'n Haqaiq ghiwamidh al-Tanzil wa U'yun al-Aqawil fi Wajuh al-Ta'wil, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995, cet.I.
Al-Zarkasyi, Badar al-Din al-Burhan fi Ulum al-Qur'an, kairo: Musthafa al-Halabi, 1957, jilid.1, cet.I,
al-Zuhaili, Mushthafa bin Wahbah al-Tafsir al-Munir fi al-A'qidah wa al-Syari'at wa al-Manhaj, Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
(DOSEN IAIN STS. JAMBI)
A. Pendahuluan
Al-Qur’an sebagai hudan li al-nas (petunjuk bagi manusia) merupakan referensi utama dalam sains keislaman. Ketika al-Qur’an dikaitkan dengan sumber ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan manusia di dunia ini, maka pada saat itu ia berada pada posisi tibyan li kulli syai (penjelasan tentang segala sesuatu) yang paling utama sebagai rujukan dalam kehidupan manusia. Sedangkan Rasulullah Saw –dalam kontek ini- merupakan referensi kedua yang menempati posisi sebagai mubayyin (Orang yang menjelaskan) mengenai maksud, tujuan dan target yang dikehendaki makna-makna tersurat dan tersirat di dalam ayat-ayat al-Qur’an. Penjelasan-penjelasan Rasulullah Saw kepada manusia tentang isi kandungan al-Qur’an dikenal dalam terma tafsir sebagai tibyan li al-nas (penjelasan bagi manusia) yang kemudian disebut dengan Hadits Rasulullah Saw . Al-Qur'an sebagai Tibyan li Kulli Syai dan Hadits Rasulullah Saw sebagai tibyan li al-nas dalam terma ilmu tafsir disebut juga dengan istilah al-tafsir bi al-ma'tsur atau al-tafsir bi al-riwayah . Oleh karena Rasulullah Saw., pada masa hidupnya melarang sahabat-sahabatnya untuk menulis hadits-haditsnya lantaran adanya kekhawatiran akan bercampur aduk dengan ayat-ayat al-Qur’an yang pada saat itu proses nuzul al-Qur’an sedang berlangsung. Maka para sahabatnya pada saat itu hanya menghafal hadits-hadits yang mereka dengar dan yang mereka saksikan langsung dari beliau sampai akhir hayatnya. Kondisi seperti ini –sebagaimana disebut dalam sejarah kodifikasi Hadits-- berlangsung hingga masa khalifah Umar bin Abdul Azis . Disamping itu, karena seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya persoalan hidup dari berbagai aspek kehidupan manusia, maka sahabat dan ulama mengambil langkah ijtihad untuk mencari makna ayat-ayat al-Qur'an, bila mereka tidak menemukan nash-nash di dalam al-Qur'an dan Hadits. Termasuk dalam hal ini, ijtihad dalam menafsirkan al-Qur'an yang dikenal dengan istilah al-tafsir bi al-dirayah atau al-tafsir bi al-ra'yi .
Al-Qur'an sebagai tibyan (penjelasan) tidak menafsirkan setiap kata, kalimat dan ayat-ayatnya secara menyeluruh melainkan hanya sebatas kata atau kalimat yang dipandang sulit untuk dipahami oleh manusia. Oleh karena itu dalam kerangka tujuan realistik dan idealistik, al-Qur'an perlu ditafsirkan ayat-ayatnya secara benar sesuai dengan makna yang sesungguhnya atau makna yang mendekati kebenaran yang dikehendaki ayat-ayat itu sendiri. Itulah sebabnya Rasulullah Saw, memberikan tafsiran terhadap ayat-ayat yang turun bila diperlukan penjelasan. Langkah seperti ini sesungguhnya diikuti oleh para sahabatnya, tabiin dan para ulama sepanjang zaman.
Adapun tujuan ilmu tafsir, menurut Muhammad Abduh, adalah merealisasikan keberadaan al-Qur’an itu sendiri sebagai petunjuk dan rahmat Allah, dengan menjelaskan hikmah dibalik makna yang terkandung di dalam ayat-ayatnya untuk mencari kebenaran atau mendekati kebenaran makna yang dikendaki oleh al-Qur’an itu sendiri . Tujuan ini dikembangkan oleh Amin al-Khulli yang menyatakan bahwa tujuan ilmu tafsir adalah melakukan kontemplasi terhadap ayat-ayat al-Qur’an sebagai Kitab bahasa Arab yang Maha Agung dan mempunyai dampak kesusastraan yang paling besar (Kitab al-Arabiyyah al-Akbar) . Selanjutnya al-Qur’an menurutnya adalah Kitab yang melanggengkan bahasa Arab dari kehancurannya, dan menjadikannya kriterium dalam penelitian tata bahasa dan sastra. Sehingga dengan demikian, pengkajian tafsir dari aspek bahasa dan sastra dalam al-Qur`an merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum melangkah penafsirannya lebih jauh ke tujuan selanjutnya . Kalau tidak demikian, menurut al-khulli, siapa pun yang melakukan penafsiran al-Qur`an tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Jadi penafsiran kontemporer, menurutnya, adalah interpretasi bahasa dan sastra yang didasarkan atas metodologi yang tepat, kelengkapan berbagai aspek, dan kesinkronan distribusi pembahasan .
Sejalan dengan ini, sebagaimana diketahui bahwa al-Qur'an banyak mengungkap kata "thaghut" dalam berbagai surah atau ayat-ayatnya. Namun tidak ada satupun ayat al-Qur'an yang menafsirkan atau menginterpretasikan makna thaghut secara rinci dan konkrit. Demikian pula kitab-kitab turats (kitab-kitab tafsir klasik) belum menyentuh penafsirannya pada tataran relitas kehidupan manusia di era globalisasi sekarang ini. Oleh sebab itu berangkat dari sinilah, maka dibutuhkan penafsiran atau interpretasi tentang thaghut melalui pendekatan hermeneutik dengan metode maudhui` untuk mengungkap makna tekstual , makna kontekstual, dan makna relevan dibalik kata itu.
Dalam kitab Mu'jam al-Mufahras li Al-fâzh al-Qur'an, ditemukan bahwa kata "al-thaghut" didalam al-Qur'an terdapat pada 5 surah, dalam 8 ayat. Akan tetapi dengan beragam derivasinya tersebar pada 27 surat, dalam 39 ayat . Kata thaghut adalah lafazh yang terdapat didalam al-Qur'an, yang diulang sebanyak delapan kali. Namun dalam tataran realitas kehidupan manusia, terutama umat Islam yang mengimani al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman hidupnya, belum banyak mengenal istilah ini, dan bahkan boleh jadi tidak sedikit diantara mereka belum pernah mendengar istilah ini. Kalau mendengar saja belum pernah, apalagi memahaminya. Oleh sebab itu, menurut penulis kata ini sebaiknya dipopulerkan dan disosialisasikan pengertian dan penafsirannya kepada masyarakat Islam, sehingga mereka tidak terjebak masuk kedalam lingkaran thaghut, atau paling tidak mereka dapat memahami makna thaghut yang dikehendaki oleh ayat-ayat al-Qur'an kemudian meninggalkan segala bentuk perbuatan, sifat-sifat dan karakternya.
B. Pengertian Thaghut
Secara etimologis (ilmu asal-usul kata) dan secara leksikal (berhubungan dengan kamus), kata thaghut (طاغوت) dalam Kamus al-Munjid,
berasal dari kata-kata: طغى يطغو طغوا وطغوا وطغوانا: artinya: جاوز القدر والحـد. (melampaui ukuran dan batas), dan kata thaghut artinya adalah setiap pangkal kesesatan, setan yang mengeluarkan dari jalan kebenaran, dan setiap sesembahan selain Allah. Al-thawaghi dan al-thawaghit adalah rumah-rumah berhala. Sedangkan dalam Kamus al-Munawwir, thaghut berasal dari akar kata: طغى يطغى طغيا و طغيانا, artinya: melampauai batas. Bisa juga dari akar kata: طغى يطغو طغوا وطغوا وطغوانا, artinya: melampaui ukuran dan batas. Sedangkan kata thaghut (طاغوت) artinya adalah berhala, setan, patung, dukun dan setiap yang disembah selain Allah Ta'ala .
Sedangkan kata thaghut dalam kamus Lisan al-Arab, menyatakan bahwa kata thaghut bisa dalam konteks tunggal dan jamak atau bisa menjadi muzakkar dan mua'nnats. Thaghut wazan-nya (timbangannya) sama dengan kata fa'aluut (فعلوت), maka disebut thaghayut (طغيوت), kemudian posisi Ya (ي) didahulukan sebelum ghain (غ) dalam keadaan berharakat fathah, dan sebelumnya juga fathah, maka jadilah thayaghut طيغوت)), lalu huruf Ya dibalik menjadi huruf alif, maka jadilah thaghut (طاغوت) jamaknya: طواغيت و طواغ : , كل مجاوز حـده فى معصـيةِ artinya: setiap yang melampaui batas dalam kemaksiatan. Hal yang hampir senada dengan penjelasan kata thaghut diatas, juga dikemukakan dalam kitab Musykilah I'rab al-Qur'an, bahwa kata thaghut (طاغوت) adalah isim musytaq dari tagha (طغى) , yang dibalik (dimodifikasi), asalnya adalah thaghayut (طغيوت) berwazan dengan fa'alut (فعلوت) seperti jabarutجبروت) ), huruf ya (ي) dibalik pada posisi ghain (غ) maka jadilah thayaghut(طيغوت) , kemudian ya dibalik lagi menjadi alif karena berharakat dan sebelumnya fathah maka jadilah thaghut(طاغوت) .
Selain dari pada itu, makna thaghut menurut John L. Esposito, dalam Insiklopedinya menyatakan bahwa: "terma thaghut, dari akar taghy ("memberontak, melanggar, atau melampaui batas"), disebut 8 kali dalam al-Qur'an, thaghut menunjukkan fokus persembahannya selain Allah, dan sering juga disebut sebagai "berhala" atau "setan", bahkan maknanya lebih luas dari pada itu" . Statement ini nampaknya cenderung mengklaim secara parsial bahwa makna thaghut hanya terfokus pada masalah teologis yang mengarah kepada persoalan peribadatan atau persembahan selain Allah.
Secara terminologis, kontekstualitas pengertian thaghut dalam tafsir al-Qur'an, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Thabari dalam kitabnya, adalah "sesuatu yang melampaui batas syariat Allah lalu disembah selain-Nya, baik dengan cara dipaksa maupun karena taat kepadanya, yang berupa manusia, setan, berhala, atau bentuk ciptaan lain" . Pengertian ini hampir sama dengan pengertian yang diungkapkan oleh John L. Esposito sebagai dikutip dari pernyataan Abu al-A'la al-Maududi yang mendifinisikan thaghut dalam tafsirnya sebagai "segala sesuatu yang melampaui batas garis yang telah ditetapkan dan merebut kekuasaan ketuhanan—bukan hanya kufur kepada Allah, tetapi juga telah memaksakan kehendaknya diatas iradah (kehendak) Allah" . Bila dicermati pengertian thaghut yang diberikan al-Thabari dan Abu al-A'la al-Maududi, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa stressing penafsiran keduanya tentang makna thaghut adalah mengarah secara parsial kepada pemahaman teologis dalam bentuk peribadatan atau bentuk penyembahan selain Allah.
Terma thaghut (طاغوت) merupakan istilah yang diungkapkan berkali-kali di dalam ayat-ayat al-Qur'an. Dalam al-Qur'an, pengertian thaghut dapat diketahui maknanya melalui tafsir yang sesuai dengan redaksi ayat-ayat yang memuat kata tersebut. Kata thaghut di dalam al-Qur'an disebutkan delapan kali di dalam 5 (lima) surah dan 8 (delapan) ayat. Masing-masing ayat memiliki makna penafsiran tekstual dan kontekstual yang beragam. Pengertian thaghut dalam surah al-Baqarah ayat 256, berarti setan , dalam surah yang sama pada ayat 257, Mujahid berkata: thaghut adalah setan dalam bentuk manusia . Pada surah al-Nisa ayat 51, thaghut berarti; tukang sihir dan dukun , dalam surah yang sama pada ayat 60, thaghut bermakna Ka'ab bin al-Asyraf seorang hakim Yahudi , pada ayat 76 dalam surah yang sama, thaghut maknanya adalah ketaatan terhadap setan . Pada surah al-Maidah ayat 60, thaghut diartikan sebagai segala sesuatu yang melampaui batas ketentuan Allah . Pada surah al-Nahl ayat 36, kata thaghut artinya adalah setiap sesuatu yang mengajak kepada kesesatan . Pada surah al-Zumar ayat 17, thaghut diartikan sebagai sesuatu yang disembah selain Allah Swt .
Deskripsi makna thaghut sebagaimana yang telah dijelaskan secara etimologis dan leksiologis oleh pakar ahli bahasa di dalam kamusnya masing-masing di atas, menurut penulis dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa secara tekstual tafsir pengertian thaghut adalah setiap perbuatan melampaui batas. Bila pengertian ini ditakhsiskan berdasarkan makna ta'wil , maka dapat disebut maknanya sebagai; setan, dukun, tukang sihir, atau berhala. Ta'wil makna tekstual seperti ini sesungguhnya telah ditafsirkan oleh para ahli tafsir klasik terdahulu. Pengertian makna seperti inilah yang banyak diungkapkan dalam kitab-kitab tafsir yang beraliran pemahaman tafsir bi al-ma'tsur. Kemudian pengertian tekstual ini terus berkembang dari masa ke masa sehingga para pakar tafsir kontemporer menginterpretasikan maknanya secara kontekstual yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.
C. Asbab al-Nuzul
Imam al-Wahidi berpendapat bahwa untuk mengetahui tafsir suatu ayat al-Qur’an, tidak mungkin tanpa mengetahui latar belakang peristiwanya dan kejadian turunnya . Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mengertahui asbab nuzul ayat, membantu dalam memahami makna ayat, karena mengetahui kejadian turunnya itu memberikan dasar untuk mengetahui penyebabnya . Dari ungkapan al-Wahidi dan Ibnu Taimiyah ini memberikan aba aba kepada setiap orang yang bermaksud menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an, agar tidak melupakan asbab al-nuzul, karena hal itu sangat membantu dalam pemahaman ayat secara benar dan komprehensif. Walaupun sesungguhnya ayat-ayat al-Qur’an secara keseluruhan tidak turun melalui asbab al-nuzul, namun dalam hal-hal tertentu tidak sedikit ayat-ayatnya yang turun melalui berbagai peristiwa atau kejadian. Misalnya ayat-ayat tentang thaghut, dari delapan ayat yang berbicara tentang kata thaghut, hanya 5 ayat yang memiliki sebab-sebab turunnya.
Kata thaghut yang terdapat pada ayat 256 surah al-Baqarah, sesungguhnya asbab nuzulnya terdapat dalam riwayat Ibnu Abbas bahwa sebelum Islam datang, ada seorang wanita yang selalu kematian anaknya. Ia berjanji kepada dirinya, apabila ia mempunyai anak dan hidup akan dijadikan Yahudi. Ketika Islam datang dan Kaum Yahudi Bani Nadhir diusir dari Madinah (karena pengkhianatannya), ternyata anak tersebut dan beberapa anak lainnya yang sudah termasuk keluarga Anshar, terdapat bersama-sama kaum Yahudi. Berkatalah kaum Anshar: “Jangan kita biarkan anak-anak kita bersama mereka (Yahudi)” . Maka turunlah ayat 256 al-Baqarah sebagai teguran bahwa tidak ada paksaan dalam Islam.
Sedangkan ayat 257 surah al-Baqarah, sebab nuzulnya ayat adalah bersumber dari riwayat yang mengemukakan bahwa ayat ini ditujukan kepada kaum yang beriman kepada Isa dan yang tidak beriman kepadanya. Setelah Muhammad Saw diutus, ada yang beriman kepada Isa dan ada juga yang kufur kepada Muhammad Saw, dan ada yang kufur kepada Isa, tapi ada juga yang beriman kepada nabi Muhammad saw .
Menurut al-Wahidi, surah al-Nisa ayat 51, turun disebabkan adanya suatu peristiwa yang terjadi setelah perang Uhud. Kaab bin al-Asyraf (orang Yahudi) datang dengan 70 pasukan berkudanya ke Mekkah untuk membatalkan perjanjian antara mereka dengan Rasulullah Saw. Kemudian Ka’ab menemui Abi Sofyan dan orang-orang Quraish: Lalu Orang-orang Quraish berkata: Kalian adalah Ahli Kitab, dan Muhammad pemilik Kitab. Kami telah aman dengan perjanjian yang penuh dengan penipuan, kalau kalian mau bersama kami, maka bersujudlah kepada dua berhala ini . Maka turulah ayat ini.
Menurut Rasyid Ridha, bahwa ayat 60 surah al-Nisa turun disebabkan oleh seorang Yahudi berselisih dengan seorang munafiq. Yahudi itu mengusulkan untuk meminta bantuan kepada Nabi dalam menyelesaikan perselisihan itu karena ia tahu bahwa Nabi tidak akan mau menerima risywah (sogokan), tetapi mereka juga sepakat untuk meminta bantuan kepada seorang pendeta di juhainah. Maka turunlah ayat ini sebagai cercaan terhadap perbuatan munafiq itu . Sedangkan menurut al-Zamakhsyari, bahwa ayat ini turun berdasarkan riwayat bahwa seorang munafiq berselisih dengan seorang Yahudi, lalu Yahudi itu mengajak menghadap kepada Rasulullah, namun munafiq itu justeru mengajak menghadap kepada Ka’ab bin al-Asyraf. Kemudian keduanya bertahkim kepada Rasulullah Saw, Yahudi itu menerimanya namun munafiq itu tidak menerimanya, lalu berkata: Mari kita berhakim kepada Umar bin Khattab, Orang Yahudi itu berkata kepada Umar: Rasulullah telah memutuskan perkara kami tetapi dia (orang munafiq itu) tidak rela dengan keputusannya, lalu Umar berkata kepada munafiq itu: apa itu benar? Dia menjawab: ya benar. Maka Umar berkata: tunggu sampai saya keluar, lalu umar masuk kesuatu tempat kemudian keluar dengan sebilah pisau lalu menebas leher munafiq tersebut dan berkata: demikianlah hukum bagi orang yang tidak menerima hukum dari Allah dan Rasulullah saw .
Adapun sebab turunnya surah al-Zumar ayat 17, dalam suatu riwayat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "الذين اجتنبوا الطاغوت" dalam ayat ini ialah Zaid bin ‘Amr bin Nafil, Abu Dzar al-Ghifari dan Salman al-Farisi di zaman Jahiliah telah mengaku bahwa “tiada Tuhan kecuali Allah” . Imam al-Wahidi berpendapat bahwa untuk mengetahui tafsir suatu ayat al-Qur’an, tidak mungkin tanpa mengetahui latar belakang peristiwanya dan kejadian turunnya . Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mengertahui asbab nuzul ayat, membantu dalam memahami makna ayat, karena mengetahui kejadian turunnya itu memberikan dasar untuk mengetahui penyebabnya . Dari ungkapan al-Wahidi dan Ibnu Taimiyah ini memberikan aba aba kepada setiap orang yang bermaksud menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an, agar tidak melupakan asbab al-nuzul, karena hal itu sangat membantu dalam pemahaman ayat secara benar dan komprehensif. Walaupun sesungguhnya ayat-ayat al-Qur’an secara keseluruhan tidak turun melalui asbab al-nuzul, namun dalam hal-hal tertentu tidak sedikit ayat-ayatnya yang turun melalui berbagai peristiwa atau kejadian. Misalnya ayat-ayat tentang thaghut, dari delapan ayat yang berbicara tentang kata thaghut, hanya 5 ayat yang memiliki sebab-sebab turunnya.
Kata thaghut yang terdapat pada ayat 256 surah al-Baqarah, sesungguhnya asbab nuzulnya terdapat dalam riwayat Ibnu Abbas bahwa sebelum Islam datang, ada seorang wanita yang selalu kematian anaknya. Ia berjanji kepada dirinya, apabila ia mempunyai anak dan hidup akan dijadikan Yahudi. Ketika Islam datang dan Kaum Yahudi Bani Nadhir diusir dari Madinah (karena pengkhianatannya), ternyata anak tersebut dan beberapa anak lainnya yang sudah termasuk keluarga Anshar, terdapat bersama-sama kaum Yahudi. Berkatalah kaum Anshar: “Jangan kita biarkan anak-anak kita bersama mereka (Yahudi)” . Maka turunlah ayat 256 al-Baqarah sebagai teguran bahwa tidak ada paksaan dalam Islam.
Sedangkan ayat 257 surah al-Baqarah, sebab nuzulnya ayat adalah bersumber dari riwayat yang mengemukakan bahwa ayat ini ditujukan kepada kaum yang beriman kepada Isa dan yang tidak beriman kepadanya. Setelah Muhammad Saw diutus, ada yang beriman kepada Isa dan ada juga yang kufur kepada Muhammad Saw, dan ada yang kufur kepada Isa, tapi ada juga yang beriman kepada nabi Muhammad saw .
Menurut al-Wahidi, surah al-Nisa ayat 51, turun disebabkan adanya suatu peristiwa yang terjadi setelah perang Uhud. Kaab bin al-Asyraf (orang Yahudi) datang dengan 70 pasukan berkudanya ke Mekkah untuk membatalkan perjanjian antara mereka dengan Rasulullah Saw. Kemudian Ka’ab menemui Abi Sofyan dan orang-orang Quraish: Lalu Orang-orang Quraish berkata: Kalian adalah Ahli Kitab, dan Muhammad pemilik Kitab. Kami telah aman dengan perjanjian yang penuh dengan penipuan, kalau kalian mau bersama kami, maka bersujudlah kepada dua berhala ini . Maka turulah ayat ini.
Menurut Rasyid Ridha, bahwa ayat 60 surah al-Nisa turun disebabkan oleh seorang Yahudi berselisih dengan seorang munafiq. Yahudi itu mengusulkan untuk meminta bantuan kepada Nabi dalam menyelesaikan perselisihan itu karena ia tahu bahwa Nabi tidak akan mau menerima risywah (sogokan), tetapi mereka juga sepakat untuk meminta bantuan kepada seorang pendeta di juhainah. Maka turunlah ayat ini sebagai cercaan terhadap perbuatan munafiq itu . Sedangkan menurut al-Zamakhsyari, bahwa ayat ini turun berdasarkan riwayat bahwa seorang munafiq berselisih dengan seorang Yahudi, lalu Yahudi itu mengajak menghadap kepada Rasulullah, namun munafiq itu justeru mengajak menghadap kepada Ka’ab bin al-Asyraf. Kemudian keduanya bertahkim kepada Rasulullah Saw, Yahudi itu menerimanya namun munafiq itu tidak menerimanya, lalu berkata: Mari kita berhakim kepada Umar bin Khattab, Orang Yahudi itu berkata kepada Umar: Rasulullah telah memutuskan perkara kami tetapi dia (orang munafiq itu) tidak rela dengan keputusannya, lalu Umar berkata kepada munafiq itu: apa itu benar? Dia menjawab: ya benar. Maka Umar berkata: tunggu sampai saya keluar, lalu umar masuk kesuatu tempat kemudian keluar dengan sebilah pisau lalu menebas leher munafiq tersebut dan berkata: demikianlah hukum bagi orang yang tidak menerima hukum dari Allah dan Rasulullah saw .
D. Tafsir Makna Thaghut
Banyaknya lafazh thaghut dan derivasinya yang terdapat dalam kadungan ayat-ayat al-Qur'an, maka konsekwensinya berakibat pada munculnya perbedaan persepsi di kalangan ulama tafsir dalam memahami, memaknai dan menginterpretasikan kata thaghut. Misalnya, kata al-Thaghut dalam surah al-Baqarah ayat 256 yang berfirman: )...فمن يكفربالطاغـوت......maka barangsiapa yang inkar kepada thaghut…) . Ayat ini mengundang perbedaan persepsi dan penafsiran dalam memahaminya. Banyak kitab-kitab tafsir yang bernuasa tafsir bi al-Ma'tsur atau tafsir bi al-dirayah menarik ayat ini kedalam persoalan teologis, dan memberikan penafsiran yang berbeda. Antara lain; Abu Ja'far al-Thabari (224H–310H) dalam kitab tafsirnya mengemukakan bahwa makna thaghut adalah sesuatu yang melampaui batas syariat, lalu disembah selain Allah, baik dengan cara dipaksa maupun karena taat kepadanya, yang berupa manusia, setan, berhala, atau bentuk ciptaan lain. Kemudian dalam penafsirannya, dia mengklasifikasikan makna thaghut dalam tiga kategori dengan merujuk pada riwayat-riwayat para sahabat, yaitu; setan, sihir dan dukun . Klasifikasi yang identik dengan ini, juga dikemukakan oleh Ibn Katsir (700 H/1300 M-774 H/1373 M) dalam kitabnya yang memaknai thaghut dengan merujuk kepada riwayat-riwayat para sahabat dan tabiin . Kelihatannya Ibn Katsir dalam menafsirkan kata thaghut cenderung mengklasifikasikan thaghut dalam tiga bentuk wujudnya yaitu; 1) dukun, 2) setan dalam bentuk manusia, dan 3) sesuatu yang disembah selain Allah. Hal yang senada dengan klasifikasi yang diberikan Ibn Katsir ini, juga diikuti oleh Jalal al-Din al-Sayuti dalam kitabnya , yang memuat riwayat-riwayat tentang thaghut. Hanya saja al-Sayuti menambahkannya riwayat dari Ibn Jarir dari Abi al-Aliyah, berkata: al-thaghut adalah tukang sihir, dan juga riwayat dari Umar bin Khattab berkata: al-thaghut adalah setan. Kelasifikasi ini kelihatannya juga diikuti oleh Mushtafa al-Hushan al-Mansuri dalam kitabnya yang menguraikan bahwa makna thaghut adalah setan, berhala dan setiap sesuatu yang disembah selain Allah.
Lain halnya dengan al-Qurtubi (w. 671 H) dalam kitab tafsirnya yang memaknai thaghut sebagai segala bentuk sembahan selain Allah, kemudian ia mengklasifikasikannya dalam empat kategori, yaitu: 1) Setan, 2) dukun, 3) berhala, dan 4) setiap yang mengajak kepada kesesatan. Seirama dengan klasifikasi ini agaknya diikuti oleh Abd al-Rahman ibn Nashir al-Sa'dy (1307 H – 1376 H) dalam kitabnya yang mengklasifikasikan makna thaghut kedalam empat kategor. 1) Sihir 2) Dukun 3) Sembahan selain Allah 4) Ketaatan pada setan. Sedangkan al-Fakhru al-Razi dalam kitabnya berpendapat bahwa selain empat kategori di atas, dia menambahkan bahwa makna thaghut adalah bentuk kedurhakaan jin dan manusia yang melampaui batas ketika berhubungan dengan sesuatu. Lalu menjadikan sesuatu ini penyebab kesesatan. Demikian pula penafsiran yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, yang berpendapat bahwa selain empat kategori di atas, dia juga menambahkan bahwa thaghut adalah kedurhakaan ahli kitab .
Beda pula dengan penafsiran yang dikemukakan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziah, sebagai dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa thaghut adalah apapun yang dilakukan manusia melampaui batas ketentuan, baik berupa sesembahan, taqlid ataupun bentuk ketaatan. Dia juga berkata: thawaghit (jama' thaghut) banyak ragamnya, namun sumbernya ada lima: Pertama, Iblis yang dilaknat Allah. Kedua, Orang yang disembah sedang ia rela. Ketiga, Orang yang mengajak manusia menyembah dirinya. Keempat, Orang yang mengaku mengetahui hal-hal ghaib. Kelima, Orang yang menghukum selain apa diwahyukan Allah. Kemudian Wahbah al-Zuhaili sendiri mengomentari pendapat Ibn al-Qayyim al-Jauziah, bahwa thaghut sesungguhnya adalah orang yang tidak kuasa mengendalikan diri terhadap persembahan batil yang melampaui batas, agar iman di dalam hati terlepas, dan bisikan nafsu syahwat terlena, seperti ambisi kekuasaan dan kekayaan atau gemar berbuat kekejian, kemungkaran, dan kezaliman . Sedangkan menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi, thaghut adalah sesuatu yang disembah dan diyakininya sebagai penyebab perbuatan melampaui batas, atau keluar dari kebenaran lantaran menyembah makhluk, baik berupa manusia, tempat sesajian, berhala, taqlid pemimpin atau hawa nafsu . Penafsiran ini agaknya sama dengan penafsiran yang diungkapkan oleh Rasyid Ridha dan Muhammad Abduh dalam kitab tafsir al-Manar Hal yang senada dengan ini, Syeikh Muhammad bin Abd. Al-Wahhab didalam risalah Ma'na al-Thaghut wa Ruusu Anwa'ihi, berpendapat bahwa tafsir makna thaghut bersifat umum, yaitu; segala sesuatu yang disembah selain Allah, dan dia rela disembah, diikuti dan ditaati diluar ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya, maka ia adalah thaghut. Kemudian dia mengklasifikasikan thaghut itu kedalam lima kategori, yaitu; 1). Setan yang mengajak beribadah selain kepada Allah. 2). Penguasa dzalim yang mengubah hukum-hukum Allah. 3). Hakim yang memutuskan perkara hukum selain apa yang disyariatkan Allah. 4). Orang yang mengaku mengetahui hal-hal ghaib. 5). Orang yang disembah selain Allah dan ia rela . Kelihatan tafsir terakhir ini cenderung mengarah kepada makna kontekstual tentang thaghut.
Dari beberapa pendapat di atas, terlihat adanya perbedaan pendapat yang signifikan di kalangan ulama dalam memahami, menafsirkan dan menginterpretasikan serta mengklasifikan kata thaghut. Sungguhpun para ulama telah membuat klasifikasi makna thaghut, bukan berarti persoalan terma ini telah ditafsirkan secara komprehensif dan tuntas. Dalam arti, masih terdapat celah-celah yang memungkinkan makna thaghut ini untuk dikaji, ditafsirkan dan diinterpretasikan kembali. Lebih-lebih bila makna thaghut dipahami sebagai lafazh yang mengandung makna umum sebagaimana kaedah tafsir yang berbunyi : العبـرة بعموم الألفاظ لا بخصـوص الأسـباب (Pemahaman lafazh suatu ayat karena redaksinya yang bersifat umum, bukan karena sebab turunnya yang bersifat khusus) . Oleh sebab itu, adanya keragaman klasifikasi thaghut yang dikemukakan oleh para ulama tafsir merupakan bukti adanya celah-celah yang masih membutuhkan penafsiran atau interpretasi yang lebih luas, jelas dan konkrit. Sebagai contoh, tafsir makna thaghut yang dikemukakan oleh al-Thabari, Ibnu Katsir dan Al-Sayuthi yang notabene tafsir bi al-ma'tsur masih menyisakan pertanyaan “apakah masih ada thaghut selain setan, dukun, tukang sihir, berhala dan setiap yang disembah selain Allah?". Lain pula halnya makna thaghut yang ditawarkan al-Qurtubi, Fakhr al-Razi dan Ibnu Taimiyah . Kelihatannya masih mengundang pertanyaan, "bagaimana sistim kinerja thaghut dalam mempengaruhi manusia sehingga masuk dalam lingkarannya?". Demikian pula makna thaghut yang ditafsirkan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, Wahbah al-Zuhaili, Musthafa al-Maraghi, Syeikh Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Muhammad bin Abd. Al-Wahhab , kelihatannya sudah mencakup penafsirannya dari berbagai aspek kehidupan manusia. Namun demikian menurut penulis masih menimbulkan pertanyaan; apakah masih bisa makna thaghut itu dikembangkan maknanya secara komprehensif, sehingga makna tekstual, kontekstual, dan relevansinya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman?, dan satu pertanyaan mendasar terhadap keragaman makna thaghut yang dikemukakan oleh para ulama tersebut yaitu; apakah kontekstualitas makna thaghut masih bisa diteliti sehingga maknanya menyentuh pada kompleksitas kehidupan manusia?. Kalaupun jawabannya “Ya”, maka masih ada tersisa pertanyaan realitis, yaitu apakah selain makna yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir klasik maupunkontemporer masih dapat dikembangkan interpretasi maknanya sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan kehidupan manusia di zaman sekarang ini?.
Bila diteliti secara cermat tingkat keragaman persepsi para ulama tafsir dalam memaknai thaghut, maka setidaknya dari penafsiran mereka itu tercermin makna esensial dan subtansial. Walaupun secara esensial tidak banyak orang yang berani dan dapat menjelaskan interpretasinya secara defenitif dan integral melalui pendekatan hermeneutik dengan menggunakan metode maudhu`i. Sedangkan secara subtansial makna thaghut dapat dipahami dan ditakhsiskan penafsirannya pada hal-hal yang lebih spesifik. Misalnya thaghut di satu sisi dapat dipahami maknanya sebagai supranatural (ghaib) seperti; setan, iblis dan sejenisnya. Di sisi lain juga bisa bermakna natural (konkrit) seperti; berhala, patung dan bentuk manusia. Dikatakan setan sebagai thaghut karena sifat-sifatnya yang cenderung melampaui batas syariat Allah, dan mengeluarkan manusia dari cahaya iman kepada kegelapan (kesesatan). Dikatakan berhala atau patung sebagai thaghut karena merupakan tempat sesajian setan yang dipergunakan manusia untuk menyembah selain Allah. Dikatakan manusia sebagai thaghut karena apa yang dilakukan dalam prakteknya bersumber dari perbuatan setan yang cenderung menyesatkan manusia dari kebenaran kepada kebatilan. Seadainya makna thaghut ditafsirkan seperti assumsi ini, maka penafsirannya mengerucut kepada pengertian yang parsial, yaitu terbatas pada persoalan teologis . Pada hal penulis dalam penelitian ini, bertujuan untuk mendalami, mengembangkan, dan memperluas makna thaghut hingga sampai pada tataran makna literal (tekstual), makna konteks (kontekstual) dan makna relevan (relevansinya dengan realitas kehidupan manusia).
Berpijak dari statemen di atas, maka objektifitas makna thaghut dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penafsirannya pada interpretasi literal (teks dan konteks) melalui kajian etimologis dan terminologis yang mengarah kepada makna leksikal, gramatikal dan historis. Sedangkan subjektifitas makna thaghut dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penafsirannya pada interpretasi monistik (makna tunggal) dan interpretasi pluralistik (makna banyak), yang mengarah pada makna relevansi dan sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi kekinian dari berbagai disiplin keilmuan.
Pada tataran realitas kehidupan manusia, sepanjang pengetahuan penulis bahwa ungkapan terma thaghut dikomunitas Islam Indonesia khususnya, belum tersosialisasi dan bahkan belum menjadi sebuah istilah yang populer terdengar. Kalaupun ada terdengar, itupun muncul sekali-kali dari pojok-pojok pesantren atau dari mulut intelektual muslim, ulama dan ustadz-ustadz saja. Hal ini terjadi, menurut asumsi penulis, disebabkan dua alternatif kemungkinan. Pertama, karena bisa saja terma ini agak sensitif dikalangan bangsa Indonesia yang dalam tanda kutip cenderung melakukan tindakan-tindakan thaghut, baik disengaja maupun tidak sengaja. Atau boleh jadi karena penafsiran makna thaghut ini belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat Islam, dan belum tersosialisasi di seluruh sektor pendidikan terutama di lembaga pendidikan Islam. Kurikiulum pendidikan agama yang diajarkan, dari sejak awal masuk madrasah atau sekolah dasar hingga di perguruan tinggi tidak pernah diajarkan ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang thaghut dengan berbagai bentuk, jenis, dan karakternya. Kedua, adalah penafsiran tentang ayat-ayat thaghut masih tersimpan di dalam kitab-kitab tafsir berbahasa Arab yang nota bene sangat sulit dipahami oleh komunitas muslim Indonesia, kecuali melalui alih bahasa kedalam bahasa Indonesia. Jika asumsi penulis di atas adalah benar, maka paradigma makna thaghut seyogyanya ditafsirkan berdasarkan makna tekstual atau kontekstual secara rinci, benar dan komprehensif, kemudian dieksposkan, dipublikasikan dan disosialisasikan diseluruh komunitas Islam melalui media cetak ataupun media elektronik agar mereka dapat memahaminya dengan benar. Dengan demikian mereka diharapkan dapat mengkufuri thaghut dan beriman kepada Allah.
Pada satu sisi, aktualisasi subjektifitas makna thaghut dalam al-Qur'an semakin menjadi urgen jika dikaitkan dengan perkembangan sosial kultural di era globalisasi dewasa ini yang dengan cara terang-terangan membawa pengaruh dampak negatif terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Aspek biologis misalnya, pengaruh thaghut sangat gencar mempengaruhi manusia agar melakukan pelanggaran asusila untuk memenuhi kebutuhan seksual. Dari aspek hukum, pengaruh thaghut sangat aktif menggerogoti pikiran para pakar hukum alias hakim dan pelindung-pelindungnya agar menyimpang dari hukum syari'at yang telah ditetapkan Allah Swt. Dari aspek kekuasaan, peran thaghut dalam mempengaruhi para penguasa dan pejabat tidak pernah menyerah agar mereka masuk dalam lingkarannya, sehingga mereka dengan mudah menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan tindakan-tindakan penyelewengan terhadap syari'at al-Qur'an. Dari aspek politik, bujukan thaghut terhadap para praktisi politik yang ambisius jabatan, semakin berpeluang mempengaruhi mereka agar melakukan berbagai macam cara yang sesat untuk mengejar tujuan tertentu. Demikian pula dari aspek ekonomi, pengaruh thaghut selalu mengajak pelaku ekonom, baik dalam skala makro maupun dalam skala mikro, agar tetap melakukan praktek riba dan penipuan dalam berbagai sistim prekonomian.
Di sisi lain, objektifitas makna thaghut sesungguhnya sudah tergambar dalam kitab-kitab tafsir, baik klasik maupun kontemporer, yang ditafsirkan melalui pendekatan tafsir bi al-ma`tsur dan tafsir bi al-ra`yi secara leksikal, semantik, dan historis. Sebagai diketahui bahwa kata thaghut di dalam al-Qur`an terpencar pada surah dan ayat yang berbeda. Hal ini memang harus diakui, sebab satu tema permasalahan dalam al-Qur`an, urutan ayat-ayat dan surahnya tidak disusun secara tematis. Tidak mengikuti sistimatika yang biasa ditulis manusia sebagai karya ilmiah. Al-Qur`an hanya memaparkan berbagai tema dalam satu bagian secara bersamaan, tidak berurutan dan kadang tidak berhubungan. Misalnya, dalam surah al-Baqarah, terdapat beragam ungkapan dan banyak rona yang mewarnai tema-tema yang berbeda, yang dijelaskan dan dilengkapi pada surah dan ayat yang lain. Namun semua itu, harus diyakini, pasti mempunyai tujuan dan hikmah dibalik itu, yang harus bisa diteliti secara ilmiah pada kajian-kajian yang memang membahas persoalan itu.
Penafsiran al-Qur`an yang mengikuti urutan ayat dan surahnya, tentu saja tidak akan memberikan pemahaman yang teliti dan pengetahuan yang benar terhadap makna dan tujuannya. Oleh sebab itu, tiada jalan lain, kecuali harus merujuk dan melengkapi penafsiran ayat al-Qur`an dengan ayat lain yang mempunyai tema senada, sehingga dengan demikian tidak terjebak dalam pemahaman parsial.
Merujuk dari assumsi inilah, maka sangat diperlukan pemahaman yang benar dan komprehensif tentang makna thaghut, melalui pendekatan hermeneutik dengan metode maudhu`i sebagai acuan kerangka berfikir dalam penafsiran al-Qur`an. Kemudian diharapkan ini dapat memberikan penyegaran makna thaghut sesuai dengan makna yang dikehendaki al-Qur’an atau paling tidak mendekati kebenaran yang dikehendaki al-Qur’an.
E. Kesimpulan
Bertitik tolak dari uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa objektifitas penafsiran makna thaghut sesungguhnya sudah tergambar dalam kitab-kitab tafsir, baik klasik maupun kontemporer, yang ditafsirkan melalui pendekatan tafsir bi al-ma`tsur dan tafsir bi al-ra`yi secara leksikal, semantik, dan historis. Jadi makna objektifitas kata thaghut adalah sesuatu yang melampaui batas ketentuan Allah Swt. Dalam tafsir dikatakan bahwa thaghut adalah setan, berhala, dukun, tukang dan setan dalam bentuk manusia. Sedangkan makna subjektifitas kata thaghut adalah segala bentuk sikap, prilaku, mental dan karakter yang ada pada manusia yang cenderung melanggar dan melampauai batas-batas syari`at yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Misalnya; penguasa zhalim, hakim zhalim, pengguna miras (ganja, narkoba dan sejenisnya), pemakan riba, pelaku zina, dan lain-lainnya yang terus menerus melakukan perbuatan maksiat dan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan syari`at Islam.
PENULIS : DRS. ABD. GHAFFAR. MA
(DOSEN IAIN STS. JAMBI)
DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA
Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya
Al-Alusi, Mahmud, Ruh al-Ma'ni fi Tafsir al-Qur'an al-Adzim wa al-Sab'i al- Matsani, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001., cet. I.
Al-Asqalani, Ibnu Hajar, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhri, Kairo: Dar al-Hadits, 2004.
Abd al-Wahhab, Muhammad, Risalah Ma'na Thaghut wa Ruusu Anwa'ihi dalam kitab Majmu' al-Tauhid, Riyadh: Maktabah al-Riyadh al-Haditsah, t,th.
Abu al-Abbas, Abd al-Halim bin Taimiyah, Daqaiq al-Tafsir al-Jami' li Tafsir Ibn Taimiyah, Damaskus: Muassasah Ulum al-Qur'an, 1404 H.
Al-Baqi, Fuad Abd, al-Mu'jam al-Mufahras li al-fâzh al-Qur'ân, Bairut: Dâr al-Ma'rifah, 1994, Cet. IV.
Al-Dzahabî, Muhammad Husain, al-Tafsîr wa al-Mufassirûn, Kairo, Maktabah al-Wahbah, 2000, cet. VII.
Al-Farmâwî, Muhammad Hijâzî, al-Bidâyah fî al-Tafsîr al-Maudhû'î, Mesir: Maktabat al-Jumhûriyyat, 1979
Ibnu Arabi (468-543H), Abi Bakar Muhammad Abdullah, Ahkam al-Qur'an li Ibn al-Arabi, Bairut: Dar al-Jil, 1987
Ibnu Katsir, Abu al-Fida' Ismail, Tafsir al-Qur'an al-Adzim (Tafsir Ibnu Katsir), Kairo: Dar al-Hadits, 1993, cet. VII.
Ibnu Taimiah, Taqiy al-Din, al-Tafsir al-Kabir li Ibn Taimiyah (Tafsir Ibnu Taimiyah), Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah
Ithr, Nur al-Din, Manhaj al-Naqd Fi Ulum al-Hadits, Bairut: Dar al-Fikr, 1398, cet. III., h. 27
John. L. Esposito, The Oxford Encyclopedia of the modern Islamic World, (New York: Oxord University Press, 1995), vol 4. John. L. Esposito, The Oxford Encyclopedia of the modern Islamic World, (New York: Oxord University Press, 1995), vol 4.
Al-Mansuri, Mushtafa al-Hushan, Al-Muqtathif Min Uyun al-Tafsir, Damaskus: Dar al-Qalam, 1996, cet. I
Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, Tafsir al-Maraghi, Kairo: Daar al-Fikr, 2006
Al-Nasafi, Ahmad bin Mahmud, Tafsir al-Nasafi yang dikenal dengan Madarik al-Tanzil wa Haqaiq al-Ta'wil, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001, cet. I.
Al-Qardhawi, Yusuf, “Metode Memahami al-Sunnah dengan Benar”. Judul asli “Kaifa Nata’ammal Ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah Ma’alim wa Dhawabith”. Pent. Saifullah Kamali, (Jakarta: Media Dakwah, 1994,)
Al-Qasimi,Muhammad Jamal al-Din, Tafsir al-Qasimi yang dikenal dengan kitab Mahasin al-Ta'wil
Qaththan, Manna', Mabahits fi Ulum al-Qur'an, Riadh: Mansyurat al-'Ashr al-Hadits, t.th, cet. III.,
Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad al-Anshari, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Kairo: Dar al-Hadits, t,th, cet. II
Quthub, Sayyid, Tafsir fi dzilal al-Qur'an, Kairo: Daar al-Syuruq, 2004
al-Razi, Fakhr al-Din, Tafsir al-Fakhr al-Razi (al-Tafsir al-Kabir wa Mafatiih al-Ghaib), Bairut: Dar al-Fikr, 2005, cet. I.
Ridha,Muhammad Rasyid, Tafsir al-Manar, Bairut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. I., 1999
Al-Sa'dy, Abd al-Rahman bin Nashir, Taisir al-Karim al-Rahman, Bairut: Muassasah al-Risalah, 1998.
Al-Sattar, Abd, Al-Madkhal fi al-Tafsir al-Maudhu'i, Kairo: Dar al-Thabaah wa al-Nasyr al-Islamiyah, 1986, cet I,
Al-Sa'di, Abd al-Rahman bin Nashir, al-Qawaid al-Hisan li Tafsir al-Qur'an, Kairo: Maktabah al-Ma'arif, t,th,.
Al-Shabuni, Muhammad Ali, al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an, Bairut: Alam al-Kutub, 1985, cet. I
Al-Sayuthi, Jalal al-Din abd al-Rahman Abi Bakar, al-Dur al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004, cet. II
Al-Sayuthi, Jalal al-Din abd al-Rahman Abi Bakar, al-Itqa fi Ulum al-Qur’an, Bairut: Dar al-Fikr, t,th, jilid I,.
Al-Syatibi, Abu Ishak, al-Muwafaqat, Bairut: Dar al-Maa'rif, 1975, cet. II.
Syarif, M.M, A History of Muslim philosophy, Delhi, Santosh offset, 1995, vol.II, cet. IV.
Shihab, M. Quraish ,Tafsir al-Misbah,
Shihab, M. Qurais, Membumikan Al-Qur’an, Bandung: Mizan, 1994, cet VI
Al-Thabari, Abu Ja'far, Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an, Bairut: Dar al-Fikr, 1405 H.,
Al-Zamakhsyari (467-538H), Mahmud bin Umar bin Muhammad, al-Kasysyaf A'n Haqaiq ghiwamidh al-Tanzil wa U'yun al-Aqawil fi Wajuh al-Ta'wil, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995, cet.I.
Al-Zarkasyi, Badar al-Din al-Burhan fi Ulum al-Qur'an, kairo: Musthafa al-Halabi, 1957, jilid.1, cet.I,
al-Zuhaili, Mushthafa bin Wahbah al-Tafsir al-Munir fi al-A'qidah wa al-Syari'at wa al-Manhaj, Bairut: Dar al-Fikr, t.th.





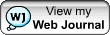
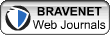


0 Coment:
Posting Komentar